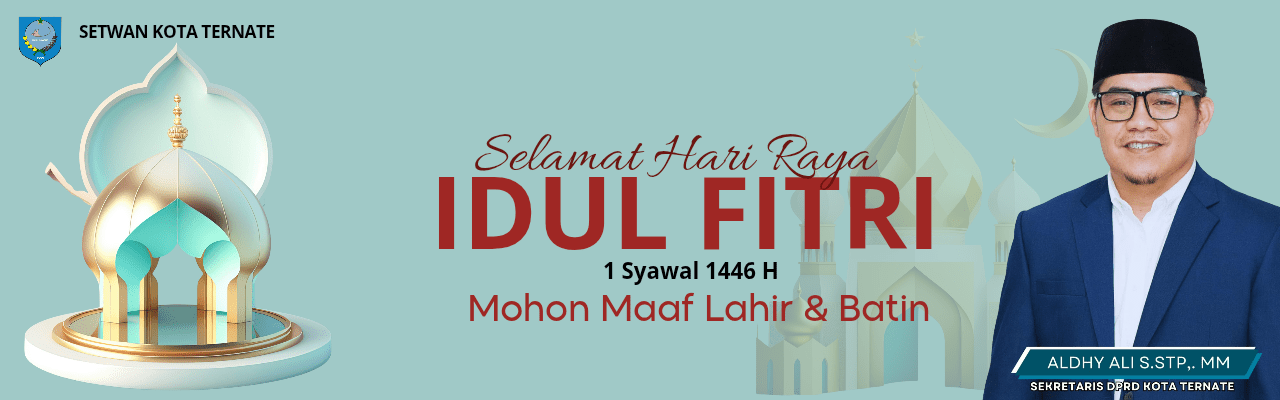Di tengah gurun yang gersang, Nabi Ayub AS pernah duduk sendiri, tubuhnya penuh luka, hartanya habis, dan keluarganya tercerai-berai. Tapi ujian kemiskinannya justru membongkar hakikat kekayaan sejati: bahwa harta harus didistribusikan secara adil, bukan ditimbun oleh segelintir orang. Sayangnya, di zaman sekarang, kita masih menyaksikan orang-orang seperti Ayub—miskin dan terluka—tetapi tanpa ada keadilan yang mengembalikan hak mereka. Kekayaan justru mengalir deras ke kantong-kantong segelintir elite, sementara rakyat biasa bergumul dengan inflasi dan kelaparan.
Jika Nabi Ayub mengajarkan kita tentang keadilan distribusi, maka Nabi Yusuf menunjukkan bagaimana mewujudkannya melalui kebijakan yang visioner. Berabad-abad kemudian, Nabi Yusuf AS membuktikan bahwa kemiskinan bisa diatasi dengan kebijakan struktural, bukan sekadar bantuan karitatif. Saat menghadapi ancaman kelaparan, ia tak hanya membagikan makanan, tapi membangun sistem logistik yang menjamin stok pangan selama tujuh tahun (QS. Yusuf: 47-49). Namun, di era modern, kita justru menyaksikan negara-negara kaya sumber daya malah mengimpor pangan karena salah urus. Gudang-gudang makanan kosong, sementara para pejabat sibuk berdebat di televisi. Seolah mereka lupa bahwa krisis pangan bukanlah takdir, melainkan buah dari kebijakan yang salah.
Warisan kebijakan pangan Nabi Yusuf ini seharusnya menjadi inspirasi bagi para pemimpin di segala zaman, termasuk Khalifah Umar yang membuktikan bahwa kepemimpinan sejati dimulai dari empati yang mendalam. Di Madinah Al-Munawwarah, Khalifah Umar bin Khattab RA pernah menangis melihat seorang ibu merebus batu untuk menipu anaknya yang kelaparan dan tidak bisa tidur. Sang Khalifah segera mengambil alih distribusi makanan dari Baitul Mal, memastikan tak ada seorang pun—masyarakatnya—yang tidur dalam kelaparan. Bisakah para pemimpin di negeri ini memastikan tidak ada lagi masyarakatnya yang kelaparan? Hari ini, di negeri-negeri yang mengaku menerapkan sistem serupa, negara melindungi fakir miskin, kita justru melihat dana sosial dikorupsi, bantuan sembako jadi alat politik, dan rakyat miskin antre berjam-jam hanya untuk mendapatkan bantuan sosial. Khalifah Umar pasti geleng-geleng kepala melihat bagaimana “keadilan” telah berubah menjadi dagelan.
Namun sejarah menunjukkan bahwa sistem yang adil pun bisa rusak ketika keserakahan merajalela, sebagaimana diperingatkan oleh Abu Dzarr dengan suaranya yang lantang.Abu Dzarr Al-Ghifari, sahabat Nabi SAW yang pemberani, pernah memperingatkan: “Jika emas dan perak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, maka tunggulah kehancuran.” Tapi di abad ke-21 ini, kita malah menyaksikan ketimpangan yang semakin menganga. Para konglomerat menumpuk harta di surga pajak, sementara buruh diupah dengan gaji yang tak cukup untuk hidup layak. Sejarah terus berulang, kemiskinan bukanlah nasib, melainkan hasil sistem yang sengaja dirancang untuk menguntungkan segelintir orang. Dan seperti di zaman Abu Dzarr, suara-suara yang protes sering dibungkam—dengan cara yang lebih halus, tapi sama kejinya.
Kemiskinan bukan sekadar persoalan pendapatan rendah, melainkan sistem multidimensi yang mencakup ketimpangan relatif, akses terbatas terhadap layanan dasar, dan dampak psikologis yang mendalam. Studi Clark (2017) dan Tauseef (2022) menunjukkan bahwa kebahagiaan lebih dipengaruhi oleh keadilan distribusi daripada pertumbuhan ekonomi semata. Di Bangladesh, ketimpangan relatif lebih menyakitkan daripada kemiskinan absolut, sementara di Peru, kelompok termarjinalkan melaporkan kebahagiaan lebih rendah meski pendapatan stabil (Mateu, 2020). Fenomena “kemiskinan eksklusif” (Zhang, 2022) memperparah penderitaan ketika masyarakat miskin terpapar gaya hidup mewah, menciptakan kompetisi sosial yang tak berujung. Kemiskinan juga merusak kesehatan mental, seperti tingginya depresi di kalangan pemuda miskin Korea Selatan (Choi, 2023), membuktikan bahwa kemelaratan bukan hanya soal uang, melainkan juga penghinaan struktural yang mengikis harga diri.
Indonesia menghadapi paradoks kemiskinan yang mengkhawatirkan: Bank Dunia mencatat 60,3% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan global, sementara BPS menyatakan angka hanya 8,57%. Perbedaan ini bukan sekadar metodologi, melainkan cerminan ketidakjujuran dalam memaknai kemiskinan. Garis kemiskinan BPS (Rp595.242/bulan) adalah lelucon pahit bagi buruh harian berpenghasilan Rp50.000/hari atau petani yang hasilnya dikeruk tengkulak. Sementara Bank Dunia mengakui 171,8 juta orang Indonesia hidup dalam ketidakpastian, Indeks Kebahagiaan Dunia 2025 menempatkan Indonesia di skor 5,6—jauh di bawah Taiwan (6,7) atau rata-rata global. Kesenjangan ini bukan hanya ekonomi, tetapi juga mencakup akses kesehatan, pendidikan, dan stabilitas sosial yang buruk, menunjukkan kegagalan sistemik dalam menciptakan kesejahteraan inklusif.
Solusi karitatif seperti bantuan sembako hanya melanggengkan ketergantungan (Ulrich, 2025), sementara kemiskinan terus diperparah oleh kebijakan yang mengabaikan akar masalah: ketidakadilan struktural. Di Maluku Utara, masyarakat adat terpinggirkan oleh tambang, sementara di perkotaan, kaum miskin terjebak dalam “kemiskinan energi”, sebagaimana meminjam temuan (Towers, 2025) yang mengungkapkan bahwa di tengah gemerlap teknologi ditemukan masyarakat yang kurang memiliki akses energi yang merata. Reformasi radikal diperlukan, bukan hanya di atas kertas, tetapi melalui redistribusi sumber daya yang adil dan pengakuan atas hak-hak dasar. Tanpa perubahan sistemik, kemiskinan akan tetap menjadi warisan kolonial yang terus diproduksi oleh rezim ekonomi-politik yang timpang, mengubur harapan jutaan orang di balik retorika pertumbuhan semu.
Kemiskinan dan Warisan Kolonial yang Tidak Kunjung Usai
Studi-studi terbaru di Mali, Papua Nugini, dan Eropa Timur (Coulibaly, 2024; Yamarak, 2023; Janikowska, 2024) mengungkap ironi pahit industri ekstraktif: meski menaikkan PDB, praktik ini justru merampas penghidupan masyarakat lokal melalui kerusakan lingkungan, penggusuran, dan ketimpangan. Di Maluku Utara, tanah adat alihfungsi untuk tambang tanpa kompensasi layak, sementara program pembangunan seperti dana desa dan CSR perusahaan gagal menjawab kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan struktural ini, sebagaimana dikatakan García-Quero (2018), adalah warisan kolonial yang dilanggengkan oleh sistem ekonomi-politik yang meminggirkan masyarakat lemah. Meski begitu, di Halmahera Timur, masyarakat adat mulai melawan, sebagaimana kritikan Schimmel (2009) bahwa kebahagiaan sejati dimulai ketika kaum tertindas menolak takdir yang dipaksakan.
Pemerintah kerap mengemas kemiskinan sebagai ” kebijakan politik” melalui bantuan karitatif seperti sembako, yang menurut Ulrich (2025) hanya memperpanjang ketergantungan. Maluku Utara menjadi simbol ironi global: penyuplai nikel untuk teknologi hijau, tetapi warganya hidup dalam “kemiskinan energi” (Towers, 2025) dan keterbelakangan. Istilah “kantong kemiskinan” pun dikritik Trojbicz (2025) sebagai pengaburan penyebab struktural, seperti korupsi dan kebijakan timpang. Mirip Mindanao di Filipina (Maboloc, 2025), kemiskinan di Maluku Utara adalah luka pembangunan tidak adil, bukan sekadar statistik. Solusi radikal hanya bergema di seminar, sementara pejabat sibuk peduli di media sosial—namun tragedi di balik gemuruh mesin tambang terus menggerus bumi di tengah kemiskinan masih menyesakkan dada.
Penulis: Aji Deni
*Dekan FISIP UMMU dan Wakil ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku Utara